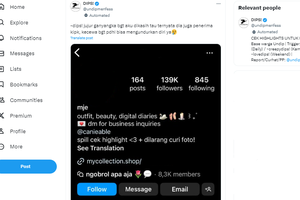Seni Menerima Kekalahan
"ORANG kita itu rindu banget prestasi timnas sepak bolanya," ujar papa saya, lelaki yang memperkenalkan permainan ini sejak saya masih sangat muda. Jamuannya pada keluarga yang datang ke Jakarta adalah Galatama. Saat mudik, ia hampir selalu pergi ke Yogyakarta atau sekitarnya untuk menyaksikan PSIM.
Sore itu, di tahun 1994, seingat saya untuk pertama kalinya saya melihat Gelora Bung Karno didatangi orang sebanyak itu saat tim nasional bertanding. Seingat saya terakhir adalah menjelang akhir 1980-an ketika Piala Kemerdekaan masih rutin tiap tahun.
Pada 1994, orang-orang datang ke stadion dengan gairah luar biasa ingin menyaksikan anak-anak muda Indonesia yang setahun terakhir menghabiskan hari-hari mereka di Genoa, Italia, untuk mengikuti kompetisi Primavera di sana.
Masih lekat di ingatan saya kejadian sekitar 27 tahun lalu itu ketika orang-orang di sepanjang koridor menuju tribune stadion berulang kali membicarakan kecepatan Kurniawan Dwi Yulianto, gol indah Ismayana Arsyad, kapten Bima Sakti, dan nama-nama lain anggota tim tersebut.
Papa saya benar, sore itu saya merasakan gairah luar biasa dari orang-orang yang datang ke stadion dan walau jumlahnya tidak memadati penjuru tribune, yang pasti dukungan besar diberikan kepada tim yang sebenarnya adalah tim junior di negeri ini, tim kelompok umur 19 tahun.
Pertandingan melawan Syria sore itu kemudian menghasilkan kekalahan untuk tim Primavera Indonesia—demikian media menyebut tim itu saat itu dan kini—skornya pun telak 0-3. Harapan kemenangan di pertandingan pertama (atas lawan yang saya sudah lupa) mendadak pun sirna dan menjadi kekhawatiran, "Mampukah kita lolos ke babak selanjutnya di turnamen itu," (pertandingan akhir pun gagal dimenangkan dan tim U19 bermateri lulusan Italia itu sama sekali tidak lolos ke mana-mana).
"Kamu sudah sering kan lihat timnas kita kalah? Ya sudah, mungkin memang sebagai orang Indonesia kita harus tahu kalau menerima kekalahan itu juga ada seninya," ujar papa saya ketika kami berjalan kaki keluar dari Kompleks GBK menuju halte bus kota.
"Seni menerima kekalahan." Iya saya masih ingat kalimat itu sampai sekarang, ketika setiap hampir semua orang selalu membicarakan tim nasional kita, ketika kejuaraan resmi sedang berlangsung.
Kita selalu merayakan kemenangan tim nasional tak peduli lawan yang kita kalahkan adalah negeri tanpa catatan sepak bola sama sekali. Memuji aksi para pemain yang turun di pertandingan itu dan kemudian yakin bahwa kita mampu menaklukkan siapa pun di Asia Tenggara dengan kemampuan berlari dan menggocek bola ala pemain kita.
Tentu saya tidak dalam posisi berkisah bahwa sejatinya sepak bola adalah permainan menggerakkan bola ke arah pertahanan lawan dan kemudian mengeksekusinya, bukan membawanya berlari sampai area lawan. Saya lebih tertarik bercerita tentang bagaimana kita ini sebenarnya sama sekali bukanlah bangsa yang dekat dengan prestasi sepak bola.
Semalam sembari ngobrol dan menghabiskan makanan di sebuah kedai di kawasan Wahid Hasyim, saya melihat bagaimana sepak bola kita ternyata masih sangat jauh dengan cara bermain yang bisa dicapai oleh Thailand.
Saya melihat bagaimana para pemain Thailand, yang bisa jadi memang lebih senior daripada kebanyakan anggota tim kita, mampu mengeksploitasi sisi-sisi lemah permainan tim dan menjadikan hal-hal macam itu sebagai kekuatan mereka.
Perbedaan besar antara Chanatip Songkrasin yang bermain di level elite Liga Jepang dipertemukan dengan pemain kasta kedua Liga Korea atau liga kawasan Balkan. Thailand mampu selalu memecahkan masalah dengan cepat ketika persoalan demi persoalan siap mengancam mereka.
Kekalahan semalam bagi saya adalah bagian dari "ritual biasa" yang sudah sering kita terima dari tim yang memang selalu konsisten di regional seperti Thailand.
Saya menyalakan gadget saya di tengah meeting semalam sudah dengan kesadaran dan kesiapan bahwa negara saya akan ditaklukkan lawan. Makanya, saya tidak tertarik-tertarik amat untuk bergabung nobar di tengah euforia jadi juara.
Saya sebagai penonton sepak bola rutin dari masa ke masa yang pernah menyaksikan Liga Hongaria atau Slovakia dan bahkan pernah menonton laga Cyprus vs Lithuania sadar bahwa sepak bola kita bukan cuma tidak ke mana-mana, tetapi memang segitu saja dari dulu.
Itulah mengapa 11 tahun terakhir ini jika negara tercinta ini sudah turun ke lapangan, mental saya sudah siap untuk menerima kekalahan.
"Kita itu jauh lebih baik dari Inggris kok, Cup," ujar Estu Ernesto kawan baik saya yang selalu bercerita tentang sepak bola dan tak ada hal lain lagi "Inggris terakhir juara tahun 1966, kita terakhir kan 1991!" katanya kemudian… Sebuah cara menerima kekalahan yang sungguh layak ditiru.
https://bola.kompas.com/read/2021/12/31/12000068/seni-menerima-kekalahan